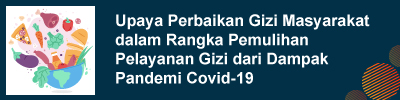Melihat dari Dekat Kasus Gizi Buruk
Jakarta – Beberapa waktu lalu, dua hari berturut-turut sebuah koran ternama Tanah Air mengulas data perihal gizi buruk yang menimpa anak Indonesia Timur. Dalam koran itu dijelaskan bahwa status gizi anak balita di wilayah timur memasuki tahap mengkhawatirkan. Wilayah yang paling tinggi terjangkit malnutrisi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Anak balita berstatus gizi buruk di NTT pada 2018 mencapai 29,5 persen. Secara nasional angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah Maluku dan Papua Barat. Bukan berarti kedua wilayah itu lebih baik, melainkan banyak kasus gizi buruk banyak tak terlaporkan.
Saya sebenarnya tidak kaget betul saat membaca data itu, karena sudah terbiasa menghadapi pemandangan malnutrisi anak di NTT secara lebih dekat. Satu tahun mengabdi menjadi relawan guru di pedalaman NTT, yakni pulau Raijua rasanya tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menceritakan kepada pembaca mengenai sekelumit persoalan akar rumput yang terjadi di wilayah paling terpelosok itu.
NTT terdiri atas pulau-pulau kecil yang menyebabkan wilayah ini rentan mendapatkan pasokan air bersih. Bahkan banyak daerah-daerah terpencil di sana yang mengalami kekeringan ekstrem. Tidak sedikit pula mata air di sumur milik warga benar-benar kering akibat kemarau panjang, menyebabkan masyarakat tidak dapat menerapkan pola hidup bersih sebagaimana diamanatkan Kementerian Kesehatan. Kondisi pelik demikian tidak hanya berdampak pada kesehatan balita melainkan memicu penyakit pada semua makhluk hidup, termasuk orang dewasa dan ternak.
Di desa Kolorae, Raijua tempat saya tinggal kurang lebih seperti itu kondisinya. Musim kemarau di sana berlangsung sekitar sembilan bulan, dan selama itu pula warga mengandalkan beras raskin dan kacang hijau untuk makan, air sumur untuk penghidupan, dan uang bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk biaya hidup. Tidak heran, setiap bulannya tidak sedikit warga yang bolak-balik ke puskesmas untuk berobat. Banyak pula ibu hamil yang kurang mengonsumsi makanan bergizi, berdampak pada kondisi anak lahir dengan berat badan rendah, dan kurus.
Sepanjang tahun lalu, cukup banyak anak-anak di sana terkena penyakit akibat tidak mendapatkan asupan gizi lengkap, bahkan satu-dua di antaranya meninggal karena diare akut. Lalu, apa saja intervensi pemerintah? Oh, tentu banyak sekali. Kucuran bantuan dana tunai dan infrastruktur kerap diberikan pemerintah pusat maupun pemda saban tahun, seperti bantuan dana PKH), KIS, dan KIP seperti yang tadi telah disebutkan.
Setiap tiga bulan sekali warga berbondong ke bank untuk mengambil bantuan sosial itu. Tidak hanya itu, setidaknya dua kali dalam satu tahun pihak sekolah juga membagikan uang Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada beberapa siswa yang berhak mendapatkannya. Selain bantuan tunai itu, warga desa juga mendapat kemudahan seperti tidak ada iuran sekolah.
Ditambah lagi, masyarakat desa juga mendapatkan bantuan berupa pembuatan waduk atau embung dari dana desa. Setiap desa sekurang-kurangnya memiliki 4 embung dengan harapan bisa menampung air hujan untuk memenuhi penghidupan warga selama musim kemarau berlangsung, walau pada kenyataannya banyak embung yang berubah menjadi kering kerontang saat memasuki pertengahan musim kemarau.
Bantuan juga tidak hanya diberikan oleh pemerintah. NTT merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki lembaga donor paling banyak. Saking banyaknya, Pulau Sumba dijuluki sebagai “Kota Seribu NGO”. Telah banyak kegiatan kemasyarakatan terutama bidang pemberdayaan ibu dan anak yang dilakukan di berbagai penjuru NTT.
Kalau dirunut kembali, berbagai kucuran bantuan sosial memang sudah banyak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Namun, mengapa daerah elok semacam NTT berada dalam urutan teratas dalam hal malnutrisi? Apa yang salah? Ke mana saja bantuan itu?
***
Secara sederhana, biaya hidup di desa sangatlah kecil dibanding di kota besar. Sekalipun hanya memiliki uang ratusan ribu, orang masih bisa bertahan hidup di desa paling terpencil. Pola kekerabatan yang kuat, solidaritas tinggi, dan penuh kekeluargaan itulah yang membuat saya bisa bertahan hidup dengan biaya minim di NTT.
Faktor kekeluargaan sangat kental di sana. Bagi mereka setiap tetangga adalah keluarga, setiap pertalian darah seperti marga atau kekerabatan yang sama akan dianggap saudara kandung. Bahkan bila seorang warga memiliki marga yang sama dengan kepala desa walau tak saling kenal, ia akan bangga menyebut “beta pung sodara itu kepala desa” –kepala desa itu saudara saya.
Nah, coba bayangkan, dalam situasi persaudaraan akut semacam itu, apapun kebijakan penyaluran bantuan sosial yang dibuat pemerintah akan sulit tepat sasaran. Di sinilah problem itu terjadi.
Elite desa menentukan arah pembangunan desa. Mereka pula menguasai berbagai gelontoran dana bantuan sosial. Kerap kali warga kesulitan mengurus bahkan tidak mendapat bantuan PKH dan bantuan lain, karena ada sentimen kemargaan maupun terjadi persoalan pribadi dengan si kepala desa. Alhasil, mereka tak dapat bantuan apa-apa sementara warga lain yang memiliki kesamaan marga, keakraban dengan elite desa justru mendapat banyak bantuan.
Contoh kasus lain kerap terjadi. Saat musyawarah desa, seorang ibu hamil muda mengomentari kebijakan desa yang keliru karena dirinya tidak mendapat dana PKH lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Usut punya usut rupanya suami si ibu tadi adalah rival politik dari si kepala desa. Pola semacam inilah yang terjadi hingga ke tataran elite pemda. Desa tertentu mendapatkan berbagai bantuan lunak, sedangkan desa lain tidak. Hal ini menjadi pangkal dari alokasi dana yang tidak tepat guna.
Begitu pula yang terjadi di sekolah. Dengan alasan “beta pung sodara”,pengelola sekolah bertindak nepotisme. Kepala sekolah memiliki wewenang penuh dalam menetapkan siapa saja anak yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Orangtua murid tentu tidak berdaya dan tidak memiliki pola pikir kritis. Sebagian besar orang desa memiliki kehalusan budi yang tinggi, sehingga untuk mengkritik pun tidak berani.
***
Saya ingin tutup tulisan ini dengan sebuah cerita. Bantuan PKH yang terus dikucurkan memang memiliki dampak positif. PKH diprioritaskan bagi keluarga fakir, ibu hamil, dan anak. Mereka pula mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Setiap tiga bulan ibu-ibu senang karena dapat uang PKH. Anak sekolah pun menikmati duit hasil pajak rakyat itu. Menariknya, sebagai seorang guru SD, saya memperhatikan pakaian anak murid, maaf, itu-itu saja seperti kucel dan kadang robek-robek. Anak-anak usia sekolahan sangat gemar membawa bumbu penyedap masakan instan ke sekolah sebagai camilan. Alis saya mengernyit bila melihat hal itu karena mereka mendapat kerap mendapat uang bantuan.
Di sisi lain, saya melihat banyak keluarga yang memiliki banyak anak. Jarak usia antaranak pun berdekatan. Iseng-iseng saya tanya ke seorang bapak rumah tangga mengapa ia memiliki banyak anak. Jawabannya bikin saya terkekeh. “Pak guru, bikin anak itu sekarang enak, dapat uang. Istri hamil dapat uang PKH. Lahiran gratis di puskesmas. Anak juga dapat uang dari PKH. Makanya tiap tahun saya bikin anak.”
Jonathan Alfrendi alumni Pengajar Muda XIV Yayasan Indonesia Mengajar, penempatan di Kabupaten Sabu Raijua NTT
(mmu/mmu)
Sumber: detik.com